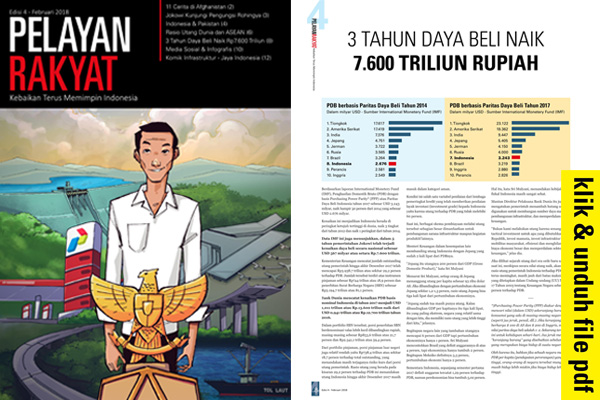Negara vs Hegemoni Neoliberalisme

Pertentangan pusat dan daerah akhir-akhir ini semakin marak dan menjadi ancaman perpecahan bangsa. Negara dalam hal ini pemerintah pusat, selama ini dianggap tidak adil dan sering menjadi kepanjangan tangan modal global dalam mengeksploitasi daerah. Kegagalan negara dalam perannya menyelesaikan konflik tidak terbatas hanya pada sektor ekonomi saja, namun juga pada sektor budaya dan kehidupan sosial lainnya.
Globalisasi bukanlah sekedar sebuah aktivitas ekonomi, dalam menciptakan pasar saja, akan tetapi dibalik globalisasi ini ada neoliberalisasi yang membawa kepentingan pasar global melakukan penetrasi ke pasar lokal. Inilah yang merupakan akar masalah konflik yang terjadi akhir-akhir ini seperti kejadian di Mesuji, Bima, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua dan hampir dibeberapa tempat di Indonesia.
Hegemoni Neoliberalisme
Argumen paling umum terhadap fenomena globalisasi adalah, tidak ada satu negarapun yang dapat melepaskan diri dari pergaulan internasional, baik disebabkan kemampuan negara dalam mencukupi kebutuhannya maupun kepentingan pasar global untuk melakukan penetrasi produk, atau kebutuhan negara lain dan industri transnasional akan bahan baku. Perubahan moda produksi turut merubah interaksi antar negara, penyediaan komoditi dan modal tidak lagi memperhatikan batas-batas negara.
Neoliberalisme yang selalu melekat dalam globalisasi adalah sebuah fenomena sosial politik yang dialamatkan kepada sekelomok penguasa dan intelektual di barat yang ingin menghidupkan kembali gagasan liberalisme klasik. Hegemoni neoliberalisme dengan kendaraan globalisasi ini mencoba menghapus batas-batas negara. Dan dalam rangka memperluas pasar dan mencari bahan baku murah maka pasar lokal seringkali berhadapan langsung dengan hegemoni neoliberalisme ini.
Hegemoni neoliberalisasi yang semakin menguat ini tidak saja menghapus batas-batas negara akan tetapi juga berusaha memperkecil peran negara. Asumsinya pasar bebas akan mencari titik kesetimbangan sendiri, sehingga efisiensi akan meningkat, regulasi yang dibuat negara hanya akan membatasi fleksibilitas pasar. Seperti dikemukakan Lenni Brenner aktivis hak-hak sipil, bahwa kehidupan ekonomi dan politik berubah, dari skala nasional menjadi skala global. Negara bertujuan untuk mendukung akumulasi kapital dengan mengaitkan lokal ke global dan menciptakan lokasi yang ideal untuk akumulasi tersebut dalam set global.
Sementara pakar sosiologi dari University of California, Berkeley. Manuel Castell mengatakan, bahwa, negara masih berperan dalam membentuk pasar melalui mediasi antara lokal dan global, dan mempengaruhi bagaimana aset khusus lokal dimobilisasi kedalam ekonomi global. Sedangkan pengamat social lainnya Immanuel Wallerstein mantan Kepala Pusat Studi Ekonomi, Sistem Sejarah dan Peradaban di Binghamton University, mengatakan, negara terintegrasi kedalam pasar melalui struktur perdagangan dan produksi internasional yang hirarkis.
Nah, kombinasi analisis diatas, merupakan proses market menuju pengorganisasian berbasis transnasional, dengan perdagangan, produksi dan finansial diorganisasikan melalui rantai komoditi global dalam ekonomi global yang terintegrasi. Pasar, negara dan masyarakat berada dalam hubungan hierarki dengan pasar yang diorganisasi secara transnasional. Jelas terlihat bahwa negara dipaksa mengambil peran sebagai kepanjangan tangan modal transnasional dan watch dog (penjaga) ideologi neoliberalisme tersebut
Persoalannya kini, adalah dominasi negara inti (Eropa Barat dan Amerika Utara) yang menguasai modal transnasional mampu mengkooptasi negara pinggiran dan menjadikan negara pinggiran hanya sebagai pasar dari produk global, dimana sumber daya alamnya terbuka seluas-luasnya untuk di eksploitasi. Dan dalam prakteknya globalisasi sering tercampur dengan internasionalisasi nilai-nilai barat yang didalamnya melekat neoliberalisme tersebut.
Praktek Neoliberalisme di Indonesia:
Pergantian pemerintahan tahun 1998 melalui gerakan sosial masyarakat yang sering dikenal sebagai Gerakan Reformasi 1998, merubah sistem pemerintahan yang otoriter menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintahan kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.
Konsekwensinya secara langsung merubah hubungan pusat dan daerah. Otonomi yang besar pada daerah sekaligus membuka daerah berhadapan langsung dengan masyarakat global. Lemahnya aturan dan regulasi mengakibatkan banyaknya produk perundang-undangan yang dihasilkan justru melemahkan peran negara (pemerintahan pusat) dalam melindungi kepentingan nasional, sekaligus kepentingan lokal. Penguatan otonomi daerah ini juga menimbulkan ketegangan baru dengan pemerintahan pusat dan mengancam kedaulatan negara. Harmonisasi produk perundang-undangan gagal menjembatani kepentingan lokal sehingga banyak produk peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang diatasnya.
Disatu sisi hegemoni neoliberalisasi dengan menumpang globalisasi, mampu mengintervensi produk perundang-undangan tersebut dan menjadikannya ramah terhadap kepentingan market global dan meninggalkan kepentingan nasional maupun lokal. Tidak saja peraturan daerah tetapi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atasnya pun tidak luput dari pengaruh global ini. Peran rent seeker (pencari rente) lebih dominan daripada birokrasi pemerintahan dan mampu mengatur aparat negara, sehingga aturan dan regulasi dibuat sedemikian rupa untuk menguntungkan modal transnasional.
Aturan dan regulasi yang tidak memihak ini memunculkan ketegangan hubungan tidak saja pada hubungan pusat dan daerah, akan tetapi juga antara masyarakat dengan kelompok kepentingan di pusat dan daerah. Korupsi yang merajalela di jajaran birokrasi turut mempercepat proses perpindahan dan penguasaan aset-aset strategis ketangan modal global. Pengelola negara (pemerintah) sering sekali lebih senang mencari jalan mudah, pelobi (lokal dan global) dan rent seeker menjadi alat efektif penetrasi global.
Kondisi ini juga mengakibatkan konflik terbuka antara masyarakat dan perusahaan yang sebagian besar merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing), bagian dari struktur finansial transnasional. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi, 2012), mencatat setidaknya 22 tempat rawan konflik masyarakat melawan perusahaan pertambanan. Bukan saja potensi konflik diramalkan akan terjadi, akan tetapi di beberapa daerah konflik telah pecah dan menimbulkan korban jiwa seperti di Mesuji (konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan PMA); di Papua (Masyarakat dan pekerja dengan perusahaan pertambangan Freeport) dan Bima (Masyarakat dengan perusahaan pertambangan).
Pilihan terhadap desentralisasi, kini kesulitannya bukan saja dikarenakan kapasitas kelembagaan ataupun sumber daya manusia (sdm) yang terbatas, akan tetapi peran yang dominan dari pelobi dan rent seeker, merupakan faktor kunci penyimpangan dari agenda besar negara menjadi agenda dalam kerangka kepentingan global semata. Secara teknis seringkali perencanaan ini dimulai dari kajian dengan menggunakan dana-dana hibah, yang merupakan entry point masuknya kepentingan global.
Salah satu prasyarat penting untuk mengatasinya, adalah melihat ulang tujuan kita bernegara, dan secara tegas melakukan koreksi kepada penyelenggara negara yang jelas-jelas berpihak, atau menjadi agen kepentingan global. Kondisi saat ini, memaksa kita merenungkan kembali cita-cita proklamasi yang bukan saja menjadi pedoman dalam upaya mensejahterakan bangsa akan tetapi berperan aktif dalam pergaulan dunia yang berkeadilan. Rasanya cita-cita ini sudah lama ditinggalkan para penyelenggara negara saat ini. Mari menjaga republik tercinta ini.
Penulis: Ammarsjah Purba

BERITA
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD,SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat, menelorkan kriteria seleksi masuk sekolah dengan mempertimbangkan urutan prioritas berupa usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya (Sistem Zonasi).
PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Namun dalam perjalananya apakah tujuan ideal dari PPDB menggunakan system zonasi tersebut sudah tercapai atau jsutru jauh panggang dari api?
Pertanyaan mendasar tentang penerapan sistem zonasi yang medasarkan pada upaya pemerataan pendidikan adalah apakah lokasi sekolah yang dibangun pemerintah sudah merata pada semua wilayah (anggaplah skala kecamatan) di Indonesia.
Bahwa faktanya pendirian sekolah (di setiap jenjang pendidikan) tidaklah didasarkan pada sebaran dan populasi penduduk, sehingga banyak dijumpai tidak meratanya sebaran sekolah di hampir setiap daerah. Satu sisi beberapa sekolah terdapat dalam satu wilayah (kecamatan), tapi banyak juga dalam satu desa/kelurahan dan kecamatan yang belum tersedia sekolah. Hal ini justru menyebabkan puluhan hingga ratusan calon peserta didik tidak mendaptkan sekolah dikarenakan “kalah” dalam konteks jarak rumah dengan sekolah yang jauh, di luar jarak zonasi yang diperkenankan.
Banyaknya calon siswa yang secara domisili jauh dari sekolah menyebabkan pupusnya kesempatan untuk bisa mengakses pendidikan secara layak, sesuai yang diamanatkan undang-undang. Fakta itu tidak saja di daerah terpencil ataupun luar jawa, bahkan di kota besar sekelas Surabaya juga masih dijumpai. Belum lagi munculnya fenomena pindah KK untuk bisa menjadi dasar untuk memenuhi kriteria zonasi. Ada yang pindah KK ke saudaranya, mencari tempat domisili (apartemen, beli/sewa rumah, dsb.) hingga tawaran pindah KK yang dilakukan oknum, calo, perantara dengan mematok tarif tertentu untuk bisa mengegolkan masuk ke sekolah yang diinginkan.
Atas polemik itu, dimuculkan kebijakan baru berupa jalur baru PPDB selain jalur zonasi, yakni jalur afirmasi (keluarga miskin), jalur prestasi (akademik) dan jalur prestasi non-akademik (olah raga, seni, budaya dsb.) yang persentasenya terus diutak-atik dengan pertimbangan yang kurang jelas. Apakah kebijakan tersebut tepat dan sesuai sasaran? .
Alih-alih memberikan solusi, tapi justru menambah permasalahan baru dalam dunia pendidikan. Awalnya sempat membuat lega dan menjadi oase bagi sebagian masyarakat yang berharap putra-putrinya tetap bisa masuk ke sekolah yang diinginkan, namun nyata justru menimbulkan permasalahan baru karena tidak semudah yang dibayangkan dalam mengakses “jalur alternatif” tersebut.
Beberapa kendala dan permasalahan ternyata sering muncul dan jadi rasan-rasan di kalangan Masyarakat terutama para ibu-ibu. Ada banyak sinyalemen dan desas-desus yang berkenbang mengenai sulitnya ditembus serta penyelewengan dari “jalur alternatif” tersebut. Jalur afirmasi khususnya bagi keluarga miskin (gakin, gamis, SKTM, KIS, KIP, dll) ternyata sulit diakses. Beberapa sekolah juga “enggan” untuk menerima dan memaksimalkan kuota untuk jalur gakin karena nantinya merka akan gratis dan tidak boleh dikenakan pungutan apapun. Ada juga kemunculan gakin baru/dadakan jelang PPDB.
Demikian halnya dengan jalur presetasi baik akademik maupun non akademik. Banyak yang merasa memenuhi kriteria, tapi dalam pengurusannya “dipersulit’ hingga batas pengajuan persyaratan yang diminta tidak bisa terpenuhi. Setali tiga uang, beberapa kabar yang beredar justru muncul anak-anak yang tiba-tiba “berprestasi” dan bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Maka muncullah banyak isu tak sedap tentang “permainan” hingga sejumlah nominal yang harus disiapkan untuk menebus jalur tersebut.
Ada pula fenomena munculnya jalur khusus, yakni “jalur rekom” yang bisa muncul mulai dari yang logis hingga yang tidak masuk akal. Yang logis semisal orang tua yang bekerja di wilayah dekat sekolah bisa meminta rekom agar anaknya bisa diterima di sekolah tersebut. Ada pula jalur rekomendasi mulai dari para pejabat di lingkup pemerintahan, maupun stakeholder pendidikan berbagai lini, yang berlangsung massif baik prodeo maupun “bertarif”. Tentunya hal tersebut berlangsung ekslusif, karen hanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses dan koneksi erat saja yang bisa memanfaatkannya.
Semua sinyalemen dan desas-desus tersebut memang sulit dibuktikan hingga ke ranah hukum namun seperti sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Sistem Zonasi dalam PPDB yang ditujukan untuk pemerataan pendidikan justru dalam prakteknya memunculkan berbagai permasalahan yang menambah carut marut permasalahan di dunia pendidikan. Amanat untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan telah gagal diwujudkan. Sudah saatnya sistem zonasi dalam PPDB dengan pertimbangan utama jarak rumah siswa dengan sekolah, dihapuskan, dikembalikan pada sekolah dengan mempertimbangkan aspek sosial kemasyakartan, kompetensi, ketersediaan kuota, prestasi, dan keadilan.
Pemerintah hendaknya melaksanakan tugas utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan lebih fokus pada penggodokan kurikulum pendidikan yang lebih canggih dan modern untuk dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sehingga potensi peserta didik dapat berkembang agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Radian Jadid
*Kepala Sekolah Rakyat Kejawan
*Wakil Sekretaris LKKNU PW Jatim
*Ketua Harian Paguyuban Angkatan 93 ITS
BERITA
Pentingnya Kemudahan Persetujuan RKAB untuk Kemajuan Industri Pertambangan

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, telah lama mengandalkan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonominya. Industri pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara serta menawarkan peluang lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan optimal, diperlukan langkah-langkah konkret yang mendukung kemajuan industri pertambangan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kemudahan dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Dasar hukum dari RKAB diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 96 tahun 2021. Dalam pasal 177 ayat (1) disebutkan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Untuk ayat (3) disampaikan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud di sini adalah Peraturan Menteri ESDM no. 10 tahun 2023 tentang Tatacara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tatacara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
RKAB merupakan dokumen resmi yang mengatur rencana kegiatan operasional dan anggaran biaya suatu perusahaan pertambangan untuk jangka waktu tertentu. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Perhapi, menyampaikan secara umum kiat sukses untuk kelancaran pembuatan laporan RKAB sampai pengesahan persetujuannya sebagai berikut:
– Siapkan perencanaan yang matang sebelum menyusun RKAB, terutama PIC/single accountability person yang bertanggung jawab dan mengkoordinir penyusunan tim RKAB.
– Pastikan kewajiban keuangan PNBP dll telah dipenuhi serta tidak ada penjaminan usaha ke Pihak lain.
– Seluruh kegiatan operasional pertambangan (OP) tetap berada dalam lingkup area feasibility studies (FS) dan AMDAL.
– Optimasi dokumen pendukung dan persyaratannya sesuai dengan Kepmen Nomor 373 Tahun 2023.
– Data sumberdaya dan cadangan harus disesuaikan, terutama laporan bersumber dari competent person Indonesia (CPI).
– Proaktif melalukan pemetaan, pendekatan dan komunikasi dengan evaluator, untuk meminta masukan terhadap hasil evaluasi sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.
Sayangnya, menurut data terakhir masih sangat banyak RKAB yang belumn disetujui oleh Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Untuk sektor batubara, dari sekitar 800-an RKAB, baru sekitar 400-an RKAB yang sudah disetujui menyisakan 400-an RKAB yang belum disetujui. Sementara, untuk komoditas mineral, sebagian besar RKAB justru masih dalam proses kajian. Lambatnya proses persetujuan RKAB menjadi sorotan oleh DPR. Pada rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR (26/3/2024), Wakil Ketua Komisi VII sempat mencecar Plt Dirjen Mineral dan Batubara terkait lambannya persetujuan RKAB ini.
Pentingnya kemudahan dalam pemberian RKAB sangatlah besar bagi kemajuan industri pertambangan di Indonesia, dan berikut ini adalah beberapa alasan mengapa hal ini menjadi krusial:
1. Mendorong Investasi
Kemudahan dalam pemberian RKAB akan menarik investasi baru ke sektor pertambangan Indonesia. Investor cenderung mencari lingkungan bisnis yang stabil dan berkepastian hukum. Dengan proses pemberian RKAB yang cepat dan efisien, investor akan merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya dalam proyek-proyek pertambangan di Indonesia.
2. Meningkatkan Produktivitas
Dengan adanya RKAB yang jelas dan terstruktur, perusahaan pertambangan dapat merencanakan kegiatan operasional mereka secara lebih efisien. Hal ini akan meningkatkan produktivitas karena memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih baik, mengurangi waktu yang terbuang, dan meningkatkan output produksi.
3. Memperkuat Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
RKAB juga memuat rencana lingkungan hidup yang harus dipatuhi oleh perusahaan pertambangan. Dengan kemudahan dalam pemberian RKAB, pemerintah dapat lebih ketat dalam mengawasi dan mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem lokal.
4. Mendorong Inovasi dan Teknologi
Proses pemberian RKAB yang lancar juga akan mendorong perusahaan pertambangan untuk mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru. Dengan adanya jaminan kepastian operasional, perusahaan cenderung lebih terbuka terhadap investasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan kerja, dan mengurangi dampak lingkungan.
5. Memberikan Manfaat Sosial dan Ekonomi
Kemudahan dalam persetujuan RKAB tidak hanya menguntungkan perusahaan dan investor, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan perekonomian secara keseluruhan. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pemberdayaan masyarakat lokal, industri pertambangan dapat menjadi motor penggerak pembangunan di daerah-daerah sekitarnya.
6. Menunjukkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
Kemudahan dalam persetujuan RKAB juga dapat menunjukkan seberapa jauh industri pertambangan di Indonesia menggunakan komponen dalam negeri atau TKDN dalam operasionalnya. TKDN adalah aspek penting dalam hal rantai pasokan di dalam negeri. TKDN memberikan pengaruh penting pada pemasaran dan pengadaan barang di masyarakat.
Bagi Pemerintah, RKAB juga dapat digunakan untuk prognosa produksi dan penjualan, mengetahui besaran PNBP yang diterima Negara, kepastian pasokan agar seimbang dengan permintaan terhadap komoditi pertambangan, dan konservasi sumber daya alam. Selain itu, RKAB juga dapat menjadi alat Pemerintah untuk memprakirakan besaran investasi sektor pertambangan. Namun terdapat beberapa resiko bila persetujuan RKAB dibiarkan Pemerintah berlarut-larut tanpa kejelasan, yaitu berpotensi menyebabkan maraknya tambang ilegal, hilangnya pendapatan Negara (PNBP), dan juga kerusakan lingkungan hidup.
Kesimpulan
Kemudahan dalam pemberian RKAB sangat penting untuk kemajuan industri pertambangan di Indonesia. Dengan proses yang cepat, efisien, dan transparan, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor pertambangan yang berkelanjutan, menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama untuk memperbaiki regulasi dan proses yang terkait dengan pemberian RKAB guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan bagi industri pertambangan di Indonesia. Oleh karena itulah, tidak seharusnya pejabat yang berinisiatif dalam mempermudah persetujuan RKAB malah dihukum.
BERITA
Hilirisasi Dinasti ala Jokowi

Dikutip detikcom dari KBBI, Senin (23/10/2023), hilirisasi berarti penghiliran atau mengolah bahan baku menjadi barang siap pakai. Tapi pengertian dalam arti Dinasti Jabatan, dimana Individu yang bisa di katakan belum matang secara kapasitas dan kapabilitas dijadikan mengemban jabatan baik itu kepala daerah ataupun ketua partai.
Kita bisa melihat sebuah tontonan yang sangat dramatis layaknya Drama Korea, dimana seorang kepala negara membuat skenario dengan kekuasaan yang dimiliki, menaikkan anak menjadi kepala daerah lalu dilanjutkan menjadi calon wakil kepala negara, untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya yang hampir habis, lewat bantuan sang paman yang kebetulan bertugas mrloloskan sang krponakan, dari jalur konstitusi yang diubah sesuai kebutuhan sang keponakan untuk menjadi Cawapres.
Belum lagi sang adik yang sebelumnya menjadi YouTubers yang sempat dilaporkan gara-gara Ucapan ‘dasar ndeso’ memang pernah dilontarkan dalam video yang berjudul #BapakMintaProyek. Video diunggah sang adik pada 27 Mei 2017 dan telah dilihat 1.442.057 kali.
Sekarang sang adik yang baru masuk di partai 2 hari pada awalnya berjualan pisang, malah di angkat menjadi ketua umum partai bunga mawar, sangat miris sebuah partai anak muda tapi pola pemilihannya ala orang tua, dimana tidak berjalannya kaderisasi di sebuah partai, yang wajib mengedepankan meritokrasi.
Seperti tidak mau kalah juga sang mantu dilibatkan menjadi kepala daerah, apakah belum cukup mempertontonkan keluarga yang seperti haus akan kekuasaan, dengan dalil demokrasi dan kepentingan bangsa.
Logika kita seperti dibolak-balik, demokrasi apakah bisa berjalan sesuai jalur dengan mengedepankan konstitusi dan pilihan rakyat? tetapi sang Ayah masih memiliki kekuasaan tertinggi dan bisa mengatur segala hal yang bisa memudahkan dan menganjurkan sesuai kepentingannya, jadi sulit untuk kita bicara netralitas,Karena conflict of interest tidak bisa dihindari.
Balik ke sebuah jargon yang selalu kita dengar hilirisasi nikel, tembaga, alumunium, bauksit, lalu Hilirisasi Digital sekarang inilah wujud nyata Hilirisasi Dinasti yang lebih mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan keluarga untuk masa kini dan nanti.
Di tambah statement Jokowi 24 Januari 2024 bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara kita bisa liat Pasal 43 ayat (1) UU HAM menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon.
Penting diketahui bahwa dalam situasi pemilihan umum, seorang presiden seharusnya menunjukkan sikap netral, tanpa memihak pihak manapun, guna memastikan jalannya proses pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan perannya sebagai pemimpin pemerintahan dan kepala negara sesuai konstitusi.
Berlandaskan peraturan perundang-undangan, UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanat terkait netralitas presiden. Misalnya, Pasal 48 ayat (1) huruf b mengharuskan KPU melaporkan seluruh tahapan pemilu kepada DPR dan Presiden
Lebih rinci, Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU Pemilu mengatur peran presiden dalam membentuk tim seleksi untuk calon anggota KPU yang diajukan ke DPR. Oleh karena itu, presiden diwajibkan menjaga netralitasnya sepanjang proses pemilu.
Penggunaan wewenang oleh presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan dalam konteks pemilihan umum, harus dihindari agar tidak terjadi pencampuran wewenang.
Pasal 17 ayat (2) huruf b UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa pencampuran wewenang mencakup tindakan di luar batas kewenangan atau bertentangan dengan tujuan yang ditetapkan.
Semoga rakyat bisa berpikir lebih jernih, hati yang tulus melihat fenomena Hilirisasi Dinasti yang sekarang ada di hadapan kita. Pilihan ada di setiap individu dan banyak yang bilang kalah dan menang kita gini-gini aja sebuah pola pikir yang harus di luruskan. Karena pilihan kita yang kita pilih akan membuat kebijakan ataupun regulasi yang bisa berpengaruh dalam hidup kita 5 tahun ke depan. Kalau salah pilih, bisa saja pajak yang naik, malah gaji yang tidak naik, ataupun kebijakan yang menguntungkan oligarki di banding rakyat pada umumnya.